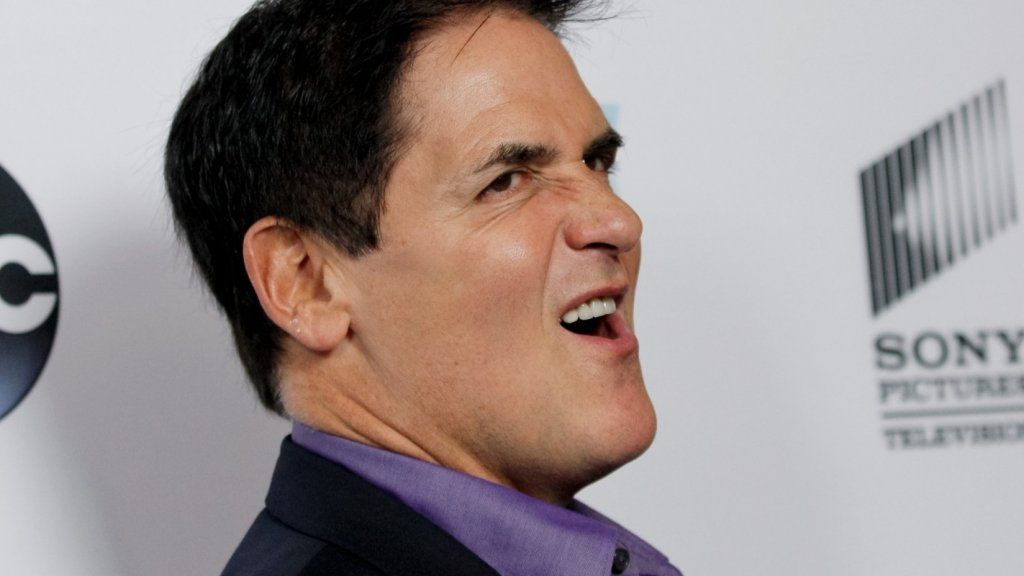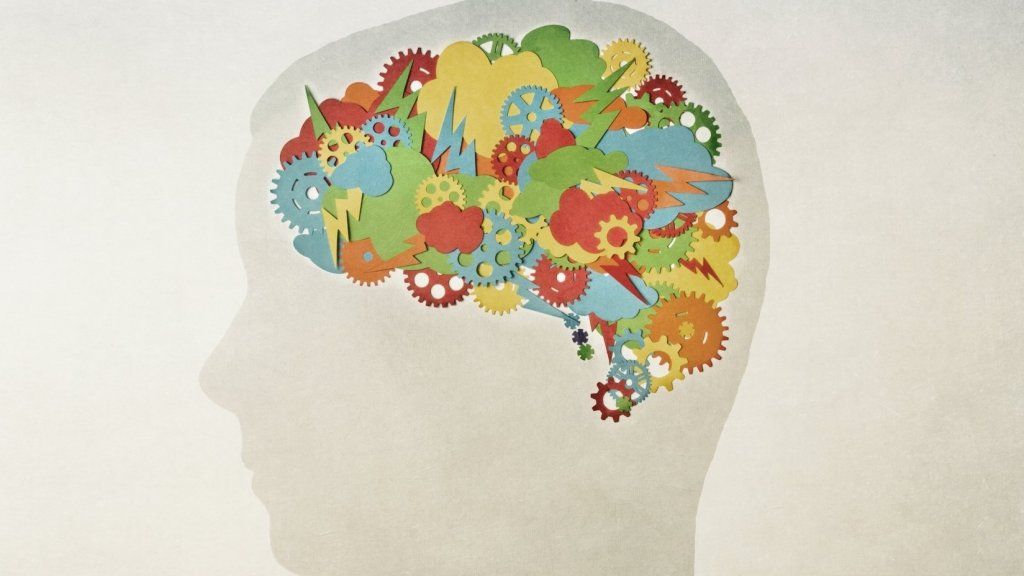Dua tahun yang lalu , Daniel Shin berhenti dari pekerjaannya dan memulai sebuah perusahaan.
Tindakan itu, dengan hampir semua standar, merupakan tindakan yang terpuji, datang seperti yang terjadi di tengah resesi terburuk dalam beberapa dekade dan mengingat bahwa Shin telah menikmati jenis kehidupan kelas menengah ke atas yang, sekali terasa, bisa jadi sulit. menyerah. Lahir di Korea Selatan, Shin pindah ke pinggiran kota Washington, D.C., bersama orang tuanya ketika dia berusia 9 tahun. Dia bersekolah di SMA magnet dan masuk ke Wharton School di University of Pennsylvania, di mana dia belajar keuangan dan pemasaran. Pada tahun 2008, ia dengan nyaman berlindung di kantor McKinsey & Company di New Jersey, di mana pengurangan era resesi berarti bahwa bacchanal Karibia yang dibayar dengan semua biaya telah memberi jalan kepada perjalanan ski yang relatif pertapa (tetapi masih semua biaya dibayar). Dia punya apartemen di Manhattan. Dia merasa nyaman. Orang tuanya bangga.
Namun entah bagaimana, kehidupan ini, dengan segala kemuliaannya yang membosankan, tidak terasa seperti miliknya sendiri. Shin adalah seorang pengusaha di hati, setelah memulai dua perusahaan saat masih kuliah. Yang pertama, sebuah situs web untuk siswa yang mencari tempat tinggal, gagal total. Yang kedua, sebuah perusahaan periklanan Internet bernama Invite Media, yang ia dirikan bersama dengan beberapa teman sekelas selama tahun seniornya, lebih menjanjikan. Ini memenangkan kompetisi rencana bisnis pada awal 2007 dan mengumpulkan $ 1 juta modal ventura pada tahun berikutnya.
Teman-teman Shin akhirnya akan menjual Invite Media ke Google seharga juta, tetapi Shin telah meninggalkan perusahaan jauh sebelum itu terjadi. Orang tuanya, yang datang jauh-jauh dari Korea justru agar putra mereka dapat tumbuh dewasa untuk bekerja di tempat seperti McKinsey, tidak akan melihat Daniel membuang kesempatan untuk memulai bisnis yang merugi yang belum pernah didengar oleh siapa pun. . 'Itulah satu-satunya alasan saya berada di McKinsey,' kata Shin. 'Itu tidak terasa seperti karir bagi saya. Saya selalu ingin memulai bisnis.'
Pada akhir 2009, Shin selesai dengan konsultasi, tapi dia belum punya nyali untuk menyerang sendiri dulu. Dia melamar, dan ditawari, pekerjaan di kantor Apax Partners, New York City, sebuah perusahaan ekuitas swasta Eropa. Dia menerima tawaran itu dengan syarat dia bisa menunda tanggal mulainya hingga Agustus berikutnya, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas dua tahun yang dia janjikan kepada McKinsey. Itu bohong; dia keluar dari McKinsey pada bulan November. 'Ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan sesuatu dari tanah tanpa orang tua saya memberi tahu saya bahwa saya tidak bisa melakukannya,' kata Shin. 'Aku punya waktu sekitar enam bulan.'
Shin mulai bekerja. Dia dan dua teman kuliahnya bersembunyi di sebuah rumah dengan papan tulis, laptop, dan persediaan McDonald's yang tak ada habisnya untuk serangkaian sesi brainstorming sepanjang hari. Tujuan mereka: untuk datang dengan bisnis yang akan tumbuh cepat dan tidak memerlukan modal awal. Mereka memulai dengan 20 ide dan, selama dua bulan, mengecilkannya menjadi satu: perusahaan kupon bergaya Groupon yang akan menawarkan penawaran restoran, acara, dan barang dagangan. Shin menyukai model bisnisnya karena memiliki strategi pembiayaan bawaan: Uang tunai datang beberapa bulan sebelum perusahaan harus membayarnya, memberinya persediaan utang gratis. Dia memilih sebuah nama—Ticket Monster—mengumpulkan beberapa ribu alamat email, dan meluncurkan situs itu pada bulan Mei.
Sebulan kemudian, Apax menelepon Shin untuk membatalkan tawaran pekerjaan. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan latar belakang dan menemukan bahwa Daniel Shin bukanlah rekanan McKinsey tahun kedua, tetapi CEO dari perusahaan yang berkembang pesat yang menghasilkan pendapatan juta per bulan. Pada akhir musim panas, Ticket Monster telah berlipat ganda, tumbuh menjadi 60 karyawan. Pada akhir tahun, perusahaan telah berlipat ganda lagi.
Ketika saya bertemu Shin Agustus lalu, hanya 20 bulan setelah dia keluar dari McKinsey, dia memiliki 700 karyawan dan pendapatan sekitar juta per bulan. 'Kami selalu takut bahwa kami tidak akan tumbuh cukup cepat,' kata Shin, seorang bayi berusia 26 tahun berwajah bayi dengan suara menggelegar dan tubuh yang besar. Setahun yang lalu, dia adalah salah satu dari hanya dua tenaga penjualan di perusahaan; hari ini, dia duduk di kantor sudut baru yang bertingkah seperti CEO. 'Kami tidak percaya menghabiskan uang di hari-hari awal,' kata Shin. 'Kami memiliki seluruh ide macho tentang memulai.' Seminggu setelah dia mengatakan ini, Shin menjual perusahaannya ke situs social-commerce LivingSocial dengan harga yang dilaporkan 0 juta.
Seorang imigran memulai bisnis, menciptakan ratusan pekerjaan, dan menjadi kaya di luar mimpi terliarnya—semua dalam hitungan bulan. Ini adalah jenis cerita satu-satunya di Amerika yang membuat kita menggelengkan kepala karena heran, bahkan bangga. Pada saat pengangguran 9 persen, itu juga jenis cerita yang sangat perlu kita dengar lebih banyak oleh orang Amerika.
Tapi Daniel Shin bukan imigran seperti itu. Dia pergi ke arah yang berlawanan. Ticket Monster berbasis di Seoul, Korea Selatan. Shin tiba di sana pada Januari 2010 dengan rencana yang tidak jelas untuk memulai sebuah perusahaan; sesi brainstorming yang menghasilkan Ticket Monster berlangsung di rumah neneknya di Seoul. Sekarang dia adalah hal yang paling dekat dengan Mark Zuckerberg Korea, terlepas dari kenyataan bahwa pada saat kedatangannya, dia hampir tidak berbicara bahasa Korea.
Desember lalu, Shin dipanggil ke Gedung Putih versi Korea Selatan—Gedung Biru—untuk bertemu dengan presiden negara itu, mantan eksekutif Hyundai bernama Lee Myung-bak. Yang hadir adalah para CEO dari banyak perusahaan terbesar di negara itu—LG, Samsung, SK, dan setengah lusin lainnya. 'Itu adalah konglomerat dan aku,' kata Shin. 'Mereka berkata, 'Kami memiliki pendapatan X miliar, dan kami berada di sejumlah negara X.' Aku seperti, 'Kami tidak ada beberapa bulan yang lalu.'' Shin tertawa—tertawa gugup dan malu—saat dia menceritakan kisah ini kepadaku dan menggelengkan kepalanya. Sudah satu setengah tahun yang gila. 'Saya pikir ini adalah pertama kalinya presiden mengetahui nama seorang pengusaha,' katanya. Beberapa minggu kemudian, Presiden Lee memberikan pidato radio di mana dia menyanyikan pujian Shin dan mendesak para pemuda Korea Selatan untuk mengikuti teladannya. (Dalam bahasa Korea, nama keluarga didahulukan sebelum nama yang diberikan. Sepanjang sisa cerita ini, saya telah menggunakan konvensi Barat, seperti halnya kebanyakan pebisnis Korea.)
Pada akhir musim panas lalu, saya melakukan perjalanan ke Seoul, sebuah kota ultra-modern berpenduduk 25 juta, karena saya ingin tahu bagaimana seorang anak berusia dua puluhan dengan uang terbatas dan kemampuan bahasa terbatas dapat menjadi harapan ekonomi besar negara ini. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi di Seoul—dan juga, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala Daniel Shin dari Wharton dan McKinsey dan McLean, Virginia. Mengapa seorang pria yang bisa dengan mudah menulis tiketnya sendiri di AS memutuskan untuk melakukannya di sisi lain dunia?
Hal pertama yang saya pelajari adalah bahwa Shin tidak sendirian—dia bahkan bukan satu-satunya orang Amerika muda yang ambisius dalam bisnis kupon. Pesaing utamanya, Coupang, didirikan oleh seorang pengusaha serial Korea-Amerika berusia 33 tahun bernama Bom Kim, yang tahun lalu keluar dari Harvard Business School dan pindah ke Seoul untuk memulai perusahaannya. Setelah lebih dari satu tahun dalam bisnis, Coupang memiliki 650 karyawan dan juta dari investor AS. Kim berharap untuk membawa perusahaan itu ke publik di Nasdaq pada 2013. 'Ada peluang di sini,' kata Kim. 'Saya ingin ini menjadi perusahaan seperti PayPal atau eBay.'
Kim adalah salah satu dari lebih dari selusin pengusaha Amerika yang saya temui di Seoul. Mereka adalah pendiri perusahaan rintisan media, perusahaan rintisan video game, perusahaan rintisan jasa keuangan, rintisan manufaktur, rintisan pendidikan, dan bahkan rintisan yang didedikasikan untuk memproduksi lebih banyak rintisan. 'Ini adalah tren besar di sini,' kata Henry Chung, direktur pelaksana DFJ Athena, sebuah perusahaan modal ventura dengan kantor di Seoul dan Lembah Silikon. 'Ada semakin banyak siswa yang belajar di luar negeri dan kembali lagi.'
Negara tempat mereka kembali adalah tempat yang sama sekali berbeda dari tempat yang mereka (atau orang tua mereka) tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Pada tahun 1961, bagian selatan semenanjung Korea—secara resmi dikenal sebagai Republik Korea—adalah salah satu tempat termiskin di dunia. Korea Selatan tidak memiliki sumber daya mineral untuk dibicarakan, dan menempati peringkat 117 di dunia dalam hal tanah yang subur per kapita, di belakang Arab Saudi dan Somalia. Lima puluh tahun yang lalu, rata-rata orang Korea Selatan hidup seperti halnya rata-rata orang Bangladesh. Hari ini, orang Korea Selatan hidup dan juga orang Eropa. Negara ini membanggakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia dengan daya beli, tingkat pengangguran hanya 3,2 persen, dan salah satu tingkat utang publik terendah di dunia. Pertumbuhan PDB per kapita Korea Selatan selama setengah abad terakhir—23.000 persen—mengalahkan China, India, dan setiap negara lain di dunia. 'Banyak orang Korea masih mengatakan bahwa pasarnya terlalu kecil,' kata Shin. 'Tapi tidak. Itu besar.'
Korea Selatan lebih kecil di daerah dari Islandia tetapi memiliki 166 kali populasi, yang berarti bahwa 80 persen dari 49 juta warganya tinggal di daerah perkotaan. Di ibukota, toko-toko ritel dan bisnis mencapai tinggi ke udara dan jauh di bawah bumi dalam mil dari pusat perbelanjaan bawah tanah. Banyak bar dan klub malam di Seoul tetap buka sampai matahari terbit, tetapi hanya berjalan di jalan-jalan kota yang sempit dan berbukit—didesak oleh pedagang asongan dan diapit oleh lampu neon yang mengiklankan tempat barbekyu dan ruang karaoke dan 'motel cinta' yang ada di mana-mana—bisa memabukkan semua orang. diri. Satu jam berkendara ke barat, di Incheon, gedung apartemen berlantai 50 dan 60 berbatasan dengan sawah dan kebun sayur.
Rasa kepadatan sesak diperbesar oleh pelukan negara teknologi komunikasi. Pada 1990-an, pemerintah Korea Selatan berinvestasi besar-besaran dalam pemasangan kabel serat optik, dengan hasil bahwa pada tahun 2000, orang Korea empat kali lebih mungkin memiliki akses Internet kecepatan tinggi daripada orang Amerika. Orang Korea masih menikmati Internet tercepat di dunia sambil membayar beberapa harga terendah. Cara termudah untuk merasa seperti orang luar di negara ini adalah dengan menaiki salah satu kereta bawah tanah Seoul, yang dilengkapi dengan Internet seluler berkecepatan tinggi, Wi-Fi, dan layanan TV digital, dan lihat di mana saja kecuali layar di tangan Anda.
Pernahkah Anda mendengar istilah Pali Pali ?' tanya Brian Park, CEO X-Mon Games, 32 tahun, yang membuat game untuk perangkat seluler. Ungkapan itu—sering diucapkan dengan cepat dan dengan volume yang cukup besar—dapat didengar di seluruh Seoul; itu diterjemahkan secara kasar menjadi 'Cepat, cepat.' Park, yang mendirikan perusahaannya pada awal tahun 2011 dengan modal awal .000 dari Ticket Monster's Shin dan .000 lainnya dari pemerintah Korea Selatan, menggunakan ungkapan itu untuk mencoba menjelaskan tiga tempat tidur yang saya perhatikan di ruang konferensi perusahaannya.
'Itu normal,' katanya, menunjuk ke rumah susun darurat. 'Budaya gila kita.' Yang dia maksud bukanlah budaya perusahaan tujuh orang. Maksudnya budaya seluruh negara Korea Selatan, di mana rata-rata pekerja menghabiskan 42 jam seminggu untuk bekerja pada tahun 2010, tertinggi di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. (Rata-rata orang Amerika bekerja 34 jam; rata-rata orang Jerman, 26.) Saya melihat pengaturan tidur yang serupa di sebagian besar perusahaan rintisan yang saya kunjungi, dan bahkan di beberapa perusahaan besar. CEO sebuah perusahaan teknologi yang beranggotakan 40 orang memberi tahu saya bahwa dia tinggal di kantornya selama lebih dari setahun, tidur di kasur lipat kecil di sebelah mejanya. Dia baru-baru ini menyewa sebuah apartemen karena investornya mengkhawatirkan kesehatannya.
Dalam kehidupan pribadi mereka, orang Korea Selatan terus memperbaiki diri, menghabiskan lebih banyak untuk pendidikan swasta—pelajaran bahasa Inggris dan menjejalkan sekolah untuk ujian masuk perguruan tinggi—daripada warga negara maju lainnya. Obsesi lain: operasi kosmetik, yang lebih umum di Korea Selatan daripada di tempat lain di dunia.
Namun terlepas dari pertunjukan luar yang dinamis ini, Korea Selatan tetap dalam jiwanya sebagai tempat yang sangat konservatif. Shin bercerita tentang pertemuan, di masa awal Ticket Monster, dengan seorang eksekutif dari konglomerat besar Korea tentang kesepakatan pemasaran. Eksekutif menolak untuk membicarakan bisnis. Dia ingin tahu mengapa seorang pria muda dengan keluarga kaya dan diploma Ivy League bermain-main dengan perusahaan baru. 'Dia mengatakan bahwa jika anaknya melakukan apa yang saya lakukan, dia tidak akan mengakuinya,' kenang Shin. Jika ini terdengar seperti hiperbola, itu bukan: Jiho Kang, yang merupakan chief technology officer dari sebuah perusahaan rintisan di California dan CEO dari perusahaan lain di Seoul, mengatakan bahwa ketika dia memulai sebuah perusahaan setelah lulus SMA, ayahnya, seorang profesor perguruan tinggi, mengusirnya dari rumah. 'Ayah saya sangat konservatif, serius Korea,' kata Kang.
Bahwa orang Korea yang lebih tua memandang pengambilan risiko dengan kecurigaan tidak mengejutkan, mengingat sejarah negara itu. Krisis keuangan Asia tahun 1997 hampir menghancurkan keajaiban ekonomi Korea Selatan. (Dalam pertunjukan ketahanan nasional yang luar biasa, warga Korea Selatan menyerahkan ratusan pon emas—ikatan pernikahan, jimat keberuntungan, pusaka—untuk membantu pemerintah mereka membayar utangnya.) Saat ini, Seoul, yang hanya berjarak 30 mil dari perbatasan Korea Utara, tetap waspada terhadap serangan nuklir atau kimia. Suatu sore ketika saya berada di Seoul, kota itu diam selama 15 menit saat sirene berbunyi dan polisi membersihkan jalan raya. Latihan-latihan ini, yang diadakan beberapa kali dalam setahun, dapat melibatkan lebih banyak lagi. Desember lalu, selusin jet tempur Korea Selatan berdengung di jalan-jalan kota untuk mensimulasikan serangan udara Korea Utara.
Di tengah semua ketidakstabilan ini, Chaebol, konglomerat milik keluarga Korea, telah menjadi benteng stabilitas, menyediakan pekerjaan terbaik, melatih generasi pemimpin baru, dan mengubah negara itu menjadi pusat kekuatan ekspor seperti sekarang ini. Chaebol tumbuh berkat kebijakan pemerintah, yang dilembagakan pada 1960-an, yang memberi mereka status monopoli di setiap industri besar. Kekuatan mereka sangat berkurang setelah krisis keuangan 1997, tetapi Chaebol masih mendominasi ekonomi. Penjualan tahun 2010 dari Chaebol terbesar Korea Selatan, Samsung Group, hampir 0 miliar, atau sekitar seperlima dari PDB negara itu.
Bagi banyak orang Korea Selatan, menjadi seorang pengusaha—artinya, menentang sistem yang membuat negara itu kaya—dipandang sebagai pemberontak atau bahkan menyimpang. 'Katakanlah Anda bekerja di Samsung dan suatu hari Anda berkata, 'Ini bukan untuk saya' dan memulai sebuah perusahaan,' kata Won-ki Lim, seorang reporter untuk Harian Ekonomi Korea . 'Saya tidak tahu bagaimana orang Amerika berpikir tentang itu, tetapi di Korea, banyak orang akan menganggap Anda sebagai pengkhianat.' Pinjaman bisnis umumnya memerlukan jaminan pribadi, dan kebangkrutan biasanya mendiskualifikasi mantan pengusaha dari pekerjaan yang baik. 'Orang-orang yang gagal meninggalkan negara ini,' kata Lim. 'Atau mereka meninggalkan industri mereka dan memulai sesuatu yang berbeda. Mereka membuka toko roti atau kedai kopi.'
Hukuman untuk kegagalan bahkan lebih berat bagi pengusaha perempuan. Ketika Ji Young Park mendirikan perusahaan pertamanya, pada tahun 1998, banknya tidak hanya memintanya untuk menjamin pinjaman perusahaan secara pribadi—permintaan yang khas untuk seorang pendiri pria—tetapi juga menuntut jaminan dari suaminya, orang tuanya, dan orang tua suaminya. Park bertahan—bisnisnya saat ini, Com2uS, adalah pengembang game ponsel senilai juta—tetapi kasusnya sangat jarang. Menurut Pemantau Kewirausahaan Global, Korea Selatan memiliki lebih sedikit wirausahawan wanita, berdasarkan per kapita, daripada Arab Saudi, Iran, atau Pakistan. 'Sebagian besar perusahaan yang diciptakan wanita sangat kecil, dan tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah,' kata Hyunsuk Lee, seorang profesor di Universitas Sains dan Teknologi Nasional Seoul.
Pengusaha di Korea Selatan sering kesulitan mengumpulkan modal. Meskipun pemodal ventura Korea menginvestasikan beberapa miliar dolar per tahun—sekitar setengahnya berasal dari kas pemerintah—sebagian besar uang masuk ke perusahaan yang mapan dan menguntungkan daripada perusahaan rintisan sejati. Bukan karena VC Korea membenci perusahaan kecil; itu hanya sulit untuk membuat uang menjual mereka. 'Chaebol tidak membeli perusahaan,' kata Chester Roh, seorang pengusaha serial dan investor malaikat yang telah mengambil satu perusahaan publik dan menjual satu ke Google. 'Mereka tidak perlu. Mereka hanya menelepon Anda dan berkata, 'Kami akan memberi Anda pekerjaan yang bagus.''
tanggal lahir cody walker
Sebagai orang Amerika, Daniel Shin tidak tunduk pada batasan ini. Investor institusi terbesarnya adalah Insight Venture Partners di New York City, di mana teman sekamar kuliahnya bekerja sebagai rekanan. 'Orang Korea Amerika memiliki keunggulan kompetitif yang besar,' kata Ji Young Park. 'Mereka dapat meningkatkan investasi yang jauh lebih besar dari luar Korea, dan mereka dapat mengambil model bisnis dari AS. Jauh lebih sulit bagi orang Korea asli.' Ini memiliki komponen budaya juga: 'Korea-Amerika tidak cenderung ke pola pikir Korea,' kata Richard Min, salah satu pendiri dan CEO Seoul Space. 'Mereka terbuka terhadap risiko.'
Min, seorang Korea-Amerika berusia 38 tahun, adalah mantan perenang perguruan tinggi yang tampaknya masih bisa melakukan beberapa putaran. Dia berpakaian bagus dan berbicara cepat, hanya dengan sedikit aksen dari negara asalnya New England. Dia meluncurkan Seoul Space tahun lalu dengan dua orang Amerika lainnya sebagai benteng kewirausahaan gaya Lembah Silikon di Seoul. Perusahaan menawarkan ruang kantor yang didiskon untuk memulai, membimbing mereka, dan kemudian memperkenalkannya kepada investor, dengan imbalan saham ekuitas kecil. 'Kami mencoba untuk membuat ekosistem berjalan di sini,' kata Min, menuntun saya melalui lautan perabot kantor yang tidak serasi di mana sekitar 20 orang muda sedang mematuk keyboard.
Min pindah ke Korea Selatan pada tahun 2001 karena dia ingin tahu tentang asal-usulnya dan karena dia melihat peluang dalam identitas gandanya. Perusahaan Korea pertamanya, Zingu, adalah perusahaan periklanan bayar per klik pertama di negara itu. Ketika kegagalan dot-com melanda Seoul, ia mengubah Zingu menjadi perusahaan konsultan untuk membantu perusahaan-perusahaan besar Korea memasarkan diri mereka di luar negeri. Dua tahun lalu, ketika peluncuran iPhone Apple di Korea memberi pengembang perangkat lunak lokal rute yang mudah ke konsumen internasional, dia memutuskan bahwa peluang besar berikutnya adalah di perusahaan rintisan. 'Anda memiliki perasaan generasi baru seperti mereka memiliki jalur yang tidak bekerja untuk Samsung,' kata Min, yang mereda biro iklannya untuk fokus pada Seoul Space. 'Kami berada di garis depan perubahan besar.'
Saya berasumsi bahwa semua orang yang bekerja di Seoul Space adalah orang Korea, tetapi ketika Min mulai memperkenalkan saya, saya menyadari bahwa setengah dari orang-orang ini adalah orang Amerika—ada Victor dari Hawaii, Peter dari Chicago, Mike dari Virginia. Yang lainnya adalah warga negara Korea tetapi dengan cara pandang Amerika yang jelas dalam memandang dunia. 'Saya adalah seorang insinyur murni—salah satu kutu buku itu,' kata Richard Choi, yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 2002, sebagai mahasiswa teknik biomedis baru di Johns Hopkins. 'Saya sama sekali tidak tertarik pada bisnis.'
Choi mengira dia akan berakhir di laboratorium beberapa perusahaan besar, tetapi ketika dia dan beberapa teman sekelasnya merancang gadget yang memudahkan teknisi medis untuk mengambil darah, dia mendapati dirinya dalam kompetisi rencana bisnis. Timnya memenangkan tempat pertama—hadiah sebesar .000—dan dia terpikat. Choi berpikir untuk memulai sebuah perusahaan setelah lulus, tetapi dia memiliki masalah: visa pelajarnya telah kedaluwarsa. Dia tidak memiliki $ 1 juta tunai yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk visa investor, jadi dia pikir satu-satunya pilihannya adalah mendapatkan pekerjaan dan berharap majikannya akan mensponsori aplikasinya untuk tinggal permanen. Dia melakukan selusin wawancara di perusahaan peralatan medis Amerika, tetapi tidak ada yang tertarik, dan dia akhirnya mendaftar di program master di Cornell untuk tinggal selama satu tahun lagi. Setelah selesai, dia menyerah pada Amerika, kembali ke Korea, dan bekerja di divisi farmasi SK, salah satu konglomerat terbesar di negara itu.
Choi bekerja di SK selama tiga tahun, tetapi dia tidak pernah menghilangkan bug kewirausahaan dari sistemnya. Karena bosan, dia memulai perusahaan pemasaran acara bernama Nodus, dan kemudian dia bertemu Min di sebuah pesta. Min memperkenalkannya kepada orang yang akhirnya (dengan satu orang lain) bersama-sama mendirikan perusahaannya saat ini, Spoqa, yang membuat aplikasi smartphone yang dirancang untuk menggantikan kartu loyalitas yang dikeluarkan oleh bisnis ritel. 'Sungguh lucu bagaimana sebuah peristiwa kecil dapat mengubah hidup Anda,' kata Choi.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah Korea Selatan telah meluncurkan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk membantu orang-orang seperti Choi. Small and Medium Business Administration—SBA versi Korea Selatan—telah menciptakan ratusan inkubator di seluruh negeri, menawarkan ruang kantor gratis kepada pengusaha, hibah ribuan dolar, dan pinjaman yang dijamin. Ada misi yang disponsori pemerintah ke Amerika Serikat dan seminar reguler untuk calon pengusaha. 'Ekonomi kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan konglomerat,' kata Jangwoo Lee, anggota Dewan Presiden untuk Masa Depan dan Visi dan profesor di Kyungpook National University di Seoul. 'Ini adalah abad ke-21. Kami membutuhkan instrumen lain untuk pertumbuhan ekonomi.'
Instrumen itu, kata Lee padaku, akan menjadi orang-orang seperti Shin. 'Dia adalah bagian dari tren baru di Korea,' kata Lee. 'Dia membuat kesuksesannya dengan ide-ide dan imajinasinya, tanpa banyak teknologi dan investasi.' Lee memberi tahu saya bahwa meskipun Korea Selatan sangat baik dalam mengkomersialkan penelitian universitas, sangat buruk dalam memelihara jenis perusahaan pengganggu yang begitu umum di AS. 'Kita perlu membuat anak muda kita bermimpi,' katanya.
Itu, kata Min, adalah ide dari Seoul Space. 'Kami berfokus untuk membantu orang memahami cara kerja berbagai hal di Lembah Silikon,' katanya. Saya merasakan hal ini pada Sabtu pagi di Seoul Space, saat saya menyaksikan setengah lusin pengusaha baru—sebagian dari Korea dan sebagian dari Amerika—menyajikan ide-ide mereka kepada 100 audiens di ruangan itu dan, melalui Skype, kepada beberapa ribu penonton di sekitar. dunia sebagai bagian dari acara TV Web yang disebut Minggu ini di Startup . Bahasa hari itu, tentu saja, bahasa Inggris, dan Min, yang telah menghabiskan waktu berjam-jam melatih enam wirausahawan di lapangan mereka, bersandar di dinding tak jauh dari kamera, menonton dengan gugup saat murid-muridnya tampil.
Di antara para presenter adalah bintang terbesar inkubator, Jaehong Kim, seorang gadis berusia 26 tahun yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam yang tingginya 8 inci di atas sepasang sepatu dua warna. Kim adalah salah satu pendiri AdbyMe, sebuah perusahaan periklanan online yang memungkinkan perusahaan di Korea Selatan dan Jepang membayar pengguna media sosial untuk menjajakan produk mereka. Dalam empat bulan pertamanya, Kim menghasilkan keuntungan saat menerima pendapatan $ 250.000 yang mengesankan.
AdbyMe lulus dari Seoul Space awal tahun ini, memindahkan 10 karyawannya ke sebuah apartemen kecil di seberang kota. Saat aku mampir di hari Senin, Kim menyuruhku melepas sepatuku, mengantarku melewati kamar tidur yang tak terhindarkan—'Aku tidur dua malam seminggu di sini,' katanya sambil tersenyum—dan kemudian memperkenalkanku pada sekelompok pria yang dia kenal. panggilan Ringo, Big I, dan AI. 'Namanya tidak benar-benar AI,' Kim menjelaskan. 'Kami saling memanggil dengan nama kode.'
Di sebagian besar perusahaan Korea Selatan—bahkan banyak perusahaan baru—karyawan disapa dengan jabatan mereka daripada nama depan mereka, tetapi Kim mencoba sesuatu yang baru. Atas saran salah satu pendirinya, seorang insinyur yang tinggal di New Orleans sebagai seorang anak, Kim memerintahkan karyawan untuk menghapus sistem tituler dan memilih nama baru. Jika mereka ingin mendapatkan perhatiannya, mereka memanggilnya bukan dengan sapaan tradisional Korea—'Mr. CEO'—tapi dengan nama panggilannya, Josh. 'Visinya adalah bahwa seorang pekerja magang dapat memberi tahu saya bahwa ada sesuatu yang tidak beres,' katanya. Saya berasumsi bahwa Kim telah dididik di AS, tetapi ternyata dia tidak langsung dari Wharton. Dia tinggal selama dua tahun di Kansas City, Kansas, tetapi pekerjaan terakhirnya adalah sebagai letnan satu di Angkatan Darat Korea.
Pada bulan September, Kim mengumpulkan 0.000 dari investor di Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan cukup untuk memenuhi syarat untuk visa investor Amerika.
Dia bukan satu-satunya pengusaha yang berbicara tentang datang ke Amerika Serikat. 'Saya tahu pasti bahwa saya ingin satu tugas lagi di Amerika,' kata Shin. Dia ingin tahu apakah dia bisa meniru kesuksesannya di pasar Amerika yang lebih besar dan lebih kompetitif; dan meskipun dia sekarang berbicara bahasa Korea yang lumayan, dia tidak pernah berhenti menganggap dirinya sebagai orang Amerika. 'Saya tidak tahu kapan, dan masih terlalu dini untuk memikirkan ide, tapi saya tahu saya mungkin akan bolak-balik,' katanya. 'Saya pikir itu mungkin untuk melakukan hal-hal di kedua tempat.'